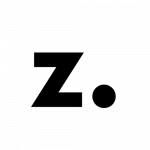Indonesia merupakan sebuah negeri yang indah, keindahan yang tak hanya terlihat dari hamparan pegunungan atau jernihnya laut biru, tetapi juga dari kekayaan ragam fauna dan flora yang hidup di dalamnya. Hutan hujan tropis kita adalah rumah bagi ratusan spesies endemik, dari burung Cenderawasih yang menari di dahan pepohonan Papua, hingga komodo yang gagah menjaga tanahnya di Nusa Tenggara Timur.
Tak berhenti di situ saja, negeri ini juga kaya akan aset hasil alam. Dari emas, tembaga, hingga uranium yang tersembunyi di perut buminya — semua adalah anugerah sekaligus tanggung jawab besar. Sumber daya ini bukan hanya milik generasi sekarang, tapi juga titipan untuk masa depan.
Jika kita tarik garis lebih jauh, Indonesia terbentang luas dari barat ke timur, begitu luasnya hingga negeri ini memiliki tiga pembagian waktu: WIB, WITA, dan WIT. Dan di antara semua itu, Waktu Indonesia Timur adalah tempat di mana matahari pertama kali menyapa bumi pertiwi setiap pagi. Ada filosofi tersendiri di dalamnya bahwa dari timurlah harapan terbit.
Namun, ironisnya, wilayah yang pertama kali menyambut matahari justru sering kali terakhir mendapat perhatian. Padahal, Indonesia Timur adalah surga yang belum banyak tersentuh, kaya akan budaya yang autentik dan bentang alam yang luar biasa. Di sinilah suara alam masih terdengar jernih, dan warisan leluhur masih hidup dalam tarian, ukiran, dan cerita lisan yang dijaga turun-temurun.
Aku pernah menyusuri keajaiban ini, dan tiap langkahku di bumi timur selalu meninggalkan jejak dalam hati.
Aku masih ingat ketika kapal kecil yang kutumpangi mulai memasuki perairan Raja Ampat. Air lautnya sebening kaca, dan di dasarnya, gugusan karang warna-warni seperti lukisan hidup. Ikan-ikan tropis berenang bebas, tak terusik. Di atas permukaan, pulau-pulau karst menjulang damai, memeluk langit biru tanpa batas.
Raja Ampat bukan sekadar tempat indah. Ia adalah ruang hidup bagi manusia dan alam yang saling bergantung. Warga lokal tidak sekadar tinggal di sana; mereka hidup selaras dengan laut. Mereka tahu kapan harus mengambil, dan kapan harus memberi kembali. Salah satu bapak nelayan pernah berkata padaku, “Kalau kita jaga laut, laut jaga kita.”
Dari Raja Ampat, aku melangkah ke Flores, menyusuri tanjakan menuju desa-desa adat yang masih berdiri teguh di pelukan alam. Di sana, Kelimutu menyambutku dengan danau kawahnya yang mistis, tiga warna berbeda dalam satu tubuh pegunungan. Tapi keajaiban terbesar justru kutemukan di Wae Rebo, desa di atas awan, tempat waktu seperti melambat dan kehidupan terasa lebih jujur.
Tenun ikat adalah bahasa diam masyarakat Flores. Setiap helainya menceritakan sejarah, mitos, dan identitas. Para ibu menenun dengan ketekunan yang tak tergesa, karena mereka tahu: budaya bukan untuk dikejar, tapi untuk dipelihara.
Lalu, aku menjejakkan kaki ke Papua tanah yang tidak sekadar luas, tapi dalam. Di Lembah Baliem, aku bertemu anak-anak suku Dani yang lincah, berlari tanpa alas kaki, dan tertawa tanpa beban. Mereka mengajarkanku bahwa kebahagiaan tidak selalu datang dari kemewahan, tapi dari rasa cukup dan keterikatan dengan tanah.
Papua adalah pelajaran tentang ketahanan dan kearifan. Hutan mereka bukan hanya penyimpan karbon dunia, tetapi juga ruang sakral. Mereka mengenal pohon seperti mengenal saudara. Mereka berburu bukan untuk berlebih, tapi untuk hidup. Mereka menghormati alam, karena alam adalah ibu bukan objek eksploitasi.
Namun, di balik semua keindahan itu, ada tantangan yang nyata.
Pariwisata yang berkembang terlalu cepat membawa ancaman: kerusakan ekosistem, ketimpangan ekonomi, hingga hilangnya nilai budaya. Sampah plastik mulai muncul di pantai yang dulu suci. Tradisi diubah menjadi tontonan, bukan penghormatan. Dan masyarakat lokal kadang hanya menjadi penonton di tanahnya sendiri.
Melalui tulisan ini, aku ingin menyampaikan sesuatu yang sederhana, tapi mendalam: jangan hanya datang untuk mengambil gambar, datanglah untuk belajar, mendengar, dan memberi kembali.
Indonesia Timur tidak butuh dikasihani. Ia butuh dihargai sebagai penjaga budaya, penyelamat ekologi, dan sumber inspirasi yang tak ternilai. Kita bisa mendukung mereka dengan memilih homestay lokal, membeli kerajinan langsung dari pembuatnya, dan menyebarkan cerita-cerita ini dengan hormat, bukan sensasi.
“Matahari dari Timur” bukan hanya tentang geografi. Ia adalah metafora tentang harapan, tentang cahaya yang bisa menerangi masa depan Indonesia jika kita menjaganya bersama. Karena sejatinya, keindahan tidak hanya untuk dinikmati, tetapi juga untuk diwariskan.
Dan dari timurlah kita bisa belajar, bahwa menjaga bumi adalah bentuk tertinggi dari cinta.